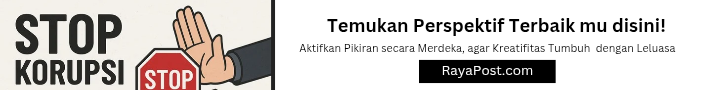Menyelamatkan Iklim melalui Restorasi Hutan
Oleh Dr. Ir. Melya Riniarti, S.P., M.Si., IPU, Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unila dan Anggota Ikaperta Unila
RayaPost.com— Raja Basa, Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis nyata yang tengah berlangsung. Tahun 2024 mencatatkan rekor suhu global tertinggi, dengan anomali suhu mencapai +1,68°C dibandingkan era pra-industri. Kenaikan suhu ini berdampak langsung pada meningkatnya kejadian cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan, yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, sektor kehutanan tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga memiliki peran sentral sebagai pilar mitigasi perubahan iklim.
Sektor Forest and Other Land Use (FOLU) merupakan tulang punggung dalam upaya Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), pemerintah menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Dari total target ini, lebih dari 60% kontribusinya diharapkan berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Oleh karena itu, arah kebijakan FOLU Net Sink 2030 menjadi langkah strategis yang tak terelakkan yang secara resmi dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2021 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
FOLU Net Sink 2030 adalah kondisi di mana jumlah emisi dari sektor kehutanan lebih kecil daripada jumlah serapan karbonnya, sehingga menghasilkan neraca emisi negatif. Strategi ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 13 tentang penanganan perubahan iklim dan SDG 15 tentang kehidupan di darat. Keduanya menekankan pentingnya konservasi ekosistem, pengelolaan hutan lestari, dan reforestasi kawasan kritis.
Restorasi hutan merupakan salah satu pilar utama dalam strategi FOLU Net Sink 2030. Meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan angka deforestasi secara signifikan (misalnya hanya 104 ribu hektare pada 2023 menurut data KLHK), kualitas ekosistem hutan yang telah terdegradasi tetap menjadi masalah serius.
Restorasi bukan hanya soal menanam kembali pohon, tetapi memulihkan fungsi ekologis kawasan. Rehabilitasi lahan kritis, restorasi ekosistem gambut, serta rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) menjadi tiga strategi utama restorasi hutan. Pemerintah menargetkan pemulihan hingga 12 juta hektare hutan dan lahan terdegradasi pada tahun 2030.
Juga menargetkan penurunan deforestrasi hingga 325.000 hektar per tahun pada 2030, berkomitmen merehabilitasi 2 juta lahan gambut yang terdegradasi.
Secara ilmiah, setiap hektare hutan tropis yang dipulihkan dapat menyerap sekitar 10 ton CO2 ekuivalen per tahun. Oleh karena itu, restorasi hutan memiliki nilai strategis sebagai solusi iklim berbasis alam yang berbiaya rendah namun berdaya serap tinggi. Selain itu, restorasi juga memberikan manfaat ekosistem tambahan seperti perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian banjir, dan peningkatan kualitas udara.
Di sisi lain, restorasi hutan juga membuka peluang ekonomi baru melalui skema perdagangan karbon. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi mekanisme perdagangan karbon kehutanan yang mulai dijalankan secara nasional. Potensi ekonomi dari sektor ini tidak kecil. Pada 2025, nilai perdagangan karbon kehutanan diperkirakan mencapai Rp 1,6–3,2 triliun per tahun, dan bisa meningkat hingga Rp 259 triliun pada 2034. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI), telah meresmikan perdagangan internasional perdana unit karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada 20 Januari 2025. Ini menandakan bahwa perdagangan karbon di Indonesia, termasuk di sektor kehutanan, semakin terintegrasi dengan pasar global.
Namun, keberhasilan restorasi dan perdagangan karbon akan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Dalam konteks ini, program Perhutanan Sosial memiliki posisi strategis, yang mencakup hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Banyak dari wilayah ini merupakan kawasan terdegradasi yang memerlukan pemulihan ekologis. Integrasi restorasi dalam Perhutanan Sosial tidak hanya mendukung mitigasi iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan agroforestry, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan, masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi pelaku utama dalam transformasi bentang alam.
Meski demikian, implementasi restorasi hutan di lapangan tidaklah mudah. Masih terdapat sejumlah tantangan seperti tumpang tindih kebijakan, keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas kelembagaan KPH, serta tekanan ekspansi komoditas seperti sawit dan tambang. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi seperti citra satelit dan drone, peningkatan kapasitas teknis, serta insentif bagi pelaku restorasi.
Restorasi hutan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Tahun 2030 tinggal beberapa langkah lagi. Kita tidak bisa hanya menanam pohon, tetapi juga harus merawat dan memulihkan hutan sebagai sistem hidup. Komitmen terhadap restorasi hutan adalah bentuk tanggung jawab kita pada generasi mendatang, serta kontribusi nyata Indonesia dalam menyelamatkan iklim global. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Prof. Emil Salim, “Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Hutan bukan musuh pembangunan, ia bagian darinya.”